Pemanfaatan sumberdaya laut baik di pesisir, di permukaan air, di kolong maupun di bawah laut sudah berlangsung sejak dahulu kala, bahkan ketika ummat manusia belum mengenal peradaban maju seperti saat ini. Laut dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhannya. Laut menjadi sumber pangan bagi manusia dan sekaligus menjadi penghubung antara satu daratan dengan daratan lainnya. Hal inilah yang mungkin menyebabkan kawasan yang paling dominan disenangi oleh manusia untuk bermukim pada awalnya juga adalah pinggir laut. Tidak heran jika kota-kota besar di dunia bahkan di Nusantara pada umumnya berada di pinggir laut. Kondisi ini menyebabkan jumlah populasi manusia terbanyak juga cenderung berada di pemukiman dekat laut.
Keberadaan populasi manusia yang banyak di dekat laut sangat erat kaitannya dengan berbagai jenis pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di laut itu sendiri. Berbagai komunitas kehidupan yang terdapat di laut, atau yang dikenal dengan ekosistem, memberikan manfaat yang beragam bagi manusia. Manfaat yang diperoleh tersebut berkembang dari waktu ke waktu seiring berkembangnya pengetahuan manusia dan kemampuannya memanfaatkan potensi yang ada.
Manfaat yang diperoleh manusia dari laut di antaranya manfaat dari segi pangan. Laut memberikan ikan dalam berbagai jenis dan ukuran yang dapat ditangkap oleh manusia sesuai dengan alat yang dipergunakannya. Selain ikan, laut juga menyediakan udang, kepiting, kerang-kerangan, dan berbagai spesies yang bisa dikonsumsi. Laut juga menyediakan bahan pangan dari tumbuhan laut yakni rumput laut, alga dan anggur laut. Bahan pangan tersebut ada yang bisa langsung dikonsumsi oleh manusia, ada pula yang dikonsumsi dalam berbagai bentuk olahan.
Terdapat berbagai produk-produk laut bernilai ekonomis penting selain pangan, yang juga sering dimanfaatkan oleh manusia. Mutiara yang bernilai jutaan bahkan puluhan juta rupiah berasal dari kerang mutiara yang banyak terdapat di laut. Selain mutiaranya, kerang mutiara juga memiliki kulit yang bisa diolah menjadi hiasan dinding yang juga bernilai jual tinggi. Terdapat pula batu karang yang dahulu banyak dimanfaatkan untuk bahan bangunan dan kapurnya untuk cat bangunan. Pasir laut sampai saat ini banyak dimanfaatkan untuk bahan bangunan rumah penduduk karena dianggap mudah diperoleh dan ekonomis.
Jasa lingkungan juga banyak diberikan oleh laut. Air laut merupakan media yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga dimanfaatkan untuk alur pelayaran. Angin laut dimanfaatkan untuk menggerakkan layar perahu nelayan, dan menggerakkan turbin untuk pembangkit tenaga listrik. Gelombang laut dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir yang juga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Keindahan alam laut yang meliputi pesisir pantai maupun panorama bawah lautnya menawarkan potensi wisata yang bernilai tinggi dan diminati masyarakat lokal sampai internasional.
Pada zaman modern saat ini kita mengenal istilah energi terbarukan yang diperoleh dari laut. Energi terbarukan tersebut berasal dari aspek fisika air laut seperti gelombang, arus dan panas air laut. Juga berasal dari aspek biologi berupa makroalga dan mikroalga. Menurut Putra (2016) Asosiasi Energi Laut Indonesia (Aseli) melansir temuan data peta potensi energi laut pada 2011. Pemetaan dilakukan pada 17 titik lokasi untuk energi panas laut, 23 titik lokasi energi gelombang laut, dan 10 titik lokasi energi arus laut. Energi terbarukan tersebut dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik dalam kapasitas yang sangat besar. Energi terbarukan dari laut menurut Nattasya (2015) selain pemanfaatan energi laut lewat arus, ombak dan panas laut, organisme laut pun sangat potensial dimanfaatkan sebagai sumber energi baru dan terbarukan. Salah satunya adalah makroalga (rumput laut) dan mikroalga (alga/ganggang), keduanya bisa diekstrak menjadi biofuel.
Laut juga memberikan berbagai jasa lingkungan untuk manusia. Laut menjadi media penghubung antara satu wilayah daratan dengan daratan lain, sehingga permukaan laut memungkinkan untuk menjadi alur pelayaran. Keindahan alam pantai, bawah laut, dan terumbu karang, memberikan pengalaman tak terlupakan untuk para wisatawan. Gelombang laut juga menawarkan pengalaman berselancar yang menyenangkan bagi para pencinta olahraga air laut.
A. Pemanfaatan Ekstraktif
Pengambilan manfaat sumberdaya perairan khususnya laut terbagi atas pemanfaatan ekstraktif dan non ekstraktif. Pengambilan manfaat dengan cara mengambil sumberdaya dikenal dengan istilah pemanfaatan ekstraktif, sedangkan pengambilan manfaat non-ekstraktif tidak dilakukan dengan mengambil sumberdaya, tetapi memanfaatkan nilai-nilai dan fungsi yang diberikan oleh sumberdaya tersebut, (CTC, 2016).
Pemanfaatan ekstraktif terhadap sumberdaya laut antara lain penambangan minyak, gas dan mineral, pengambilan batu karang pengambilan pasir dan sebagainya. Pemanfaatan dengan mengambil sumberdaya yang umum kita kenal di antaranya penangkapan ikan, udang, kerang, kepiting, lobster, teripang dan segala biota perairan, termasuk penebangan pohon mangrove. Selain itu budidaya perairan seperti budidaya ikan, budidaya mutiara, budidaya rumput laut dan jenis budidaya laut lainnya. Hal yang paling mudah dikenali dari kegiatan pemanfaatan ekstraktif adalah jika kegiatan pemanfaatan tersebut mengambil sumberdaya laut maka hal tersebut adalah kegiatan ekstraktif, terlepas dari apakah sumber asal (benih) atau terdapat bagian proses dari sumberdaya yang diambil tersebut berasal dari daratan.
- Panambangan minyak, gas, dan mineral
Pemanfaatan sumberdaya laut berupa pertambangan migas adalah kegiatan yang menggunakan teknologi maju. Potensi sumberdaya migas dan mineral di laut memiliki peluang dan tantangan. Jurnal Maritim (2015) dalam Puryono (2016), menyebutkan bahwa Komite Eksplorasi Migas Nasional memperkirakan cadangan potensial migas di Indonesia masih sekitar 222 miliar barel. Hal tersebut adalah peluang besar untuk pembangunan bangsa tetapi sekaligus menjadi tantangan karena keterbatasan teknologi untuk melakukan pengeboran gas di laut dalam, ditambah lagi perbedaan geografis dan kedalaman laut terutama di wilayah timur Indonesia.
Masyarakat pesisir sejak dahulu sudah dekat dengan keberadaan karang di laut. Bagi masyarakat pesisir, batu karang merupakan bahan bangunan yang ekonomis untuk membangun rumah, jembatan dan sebagainya. Selain untuk bangunan, kapur batu karang di sebagian masyarakat pesisir digunakan sebagai cat pemutih pada dinding rumah dan bangunan lainnya, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Maluku dan Papua. Di sebagian daerah batu karang diambil kapurnya untuk dikonsumsi (sebagian masyarakat Papua senang mengkonsumsi sirih dan pinang yang dibumbui kapur yang sebagian berasal dari karang laut). Pengambilan batu karang terus berlangsung sampai saat ini di berbagai daerah pesisir, dan terus meningkat seiring bertambahnya alasan pengambilannya. Belakangan ini sebagian nelayan mengambil batu karang dengan tujuan mengambil ikan hias yang terdapat di dalam sela-sela karang tersebut. Bahkan awal tahun 2017 terjadi penyelundupan karang di Lombok dalam jumlah ribuan kantong terumbu karang dalam berbagai jenis dengan nilai jual tinggi (Mataramnews, 2017).
Penangkapan ikan merupakan aktivitas yang paling umum ditemui di pesisir dan laut. Nelayan menggunakan berbagai alat untuk menangkap ikan. Berbagai jenis ikan ditangkap oleh nelayan untuk tujuan konsumsi dan dijual. Alat-alat tangkap dioperasikan oleh nelayan dalam berbagai jenis dan ukuran. Tombak adalah alat tangkap ikan yang paling tua dan sudah digunakan sejak zaman berburu. Pancing merupakan teknologi yang sudah cukup maju, sedangkan jaring adalah teknologi yang lebih maju lagi. Pada era modern, teknologi penangkapan ikan semakin berkembang pesat, ditandai dengan munculnya berbagai modivikasi alat tangkap ikan, semisal jaring dikembangkan menjadi pukat, pancing dikembangkan menjadi rawai dan longline. Seiring dengan perkembangan alat tangkap, armada penangkapan juga semakin meningkat dalam kapasitasnya. Abad 21 penangkapan ikan memasuki kondisi memprihatinkan, dimana terjadi penangkapan berlebihan (overfishing) di mana-mana. Overfishing tersebut disebabkan oleh upaya penangkapan ikan yang berlebihan baik dalam jumlah alat, jumlah armada penangkapan, maupun jenis-jenis alat tangkap ikan yang dioperasikan.
Mangrove yang banyak tumbuh di pesisir pantai merupakan sumber utama kayu bakar bagi masyarakat nelayan, sebelum bahan bakar minyak mudah diakses. Bahkan di beberapa tempat saat ini mangrove masih ditebangi untuk berbagai kebutuhan selain sebagai kayu bakar. Sebagian pembudidaya rumput laut mengambil mangrove untuk dijadikan pancang budidaya rumput laut. Mangrove juga sering diambil untuk pembuatan jembatan, tiang rumah dan sebagainya. Selain batang pohon mangrove, buah mangrove juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pangan seperti jus mangrove, manisan mangrove, daun mangrove jenis tertentu juga dimanfaatkan untuk obat-obatan.
Budidaya ikan sangat potensial dilakukan di perairan laut karena laut merupakan tempat hidup yang sangat baik untuk ikan. Ikan yang potensial dibudidayakan di laut sangat banyak jenisnya tergantung kemampuan biaya dari pembudidaya untuk pengadaan sarana dan prasarana budidaya. Komoditas yang banyak dibudidayakan saat ini di antaranya beberapa jenis kerapu, kuwe, lobster, dan beberapa jenis ikan hias laut. Komoditas ikan tuna juga sudah mulai dibudidayakan oleh masyarakat. Budidaya ikan di laut mengambil manfaat dari sumberdaya dengan cara mengambil sumberdaya berupa ikan tersebut. Dari aktivitas budidaya ikan di laut tersebut, masyarakat bisa memperoleh keuntungan ekonomis yang sangat besar dan mendukung pertumbuhan ekonomi keluarga melalui penjualan ikan hasil budidaya.
Teripang merupakan salah satu komoditas perairan pantai yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Teripang diambil sebagai bahan pangan, untuk dikonsumsi masyarakat, atau dijual di pasar lokal sampai pasar global. Teripang dikenal mengandung berbagai nutrisi tinggi sehingga belakangan dimanfaatkan juga untuk bahan kosmetik dan obat-obatan. Di berbagai daerah populasi teripang telah mengalami penurunan jumlah populasi. Penurunan populasi teripang di antaranya disebabkan oleh penangkapan berlebihan dan karena kerusakan habitatnya, baik oleh pengeboman atau penggunaan bahan penangkapan yang merusak maupun karena kerusakan ekosistem oleh adanya reklamasi pantai.
Rumput laut terdapat dalam beberapa jenis yang umumnya dibudidayakan oleh masyarakat pesisir seperti Gracillaria dan Euchema Cottonii. Komoditas rumput laut memiliki nilai jual yang cukup tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sumberdaya rumput laut berada di perairan sejak dari bibit sampai panen. Pertumbuhan rumput laut banyak dipengaruhi oleh nutrisi yang terbawa oleh arus air laut. Rumput laut yang dibudidayakan masyarakat merupakan sumber pangan yang memiliki manfaat beragam, utamanya untuk dikonsumsi dalam bentuk makanan jadi. Rumput laut juga diolah menjadi bahan kosmetik dan obat-obatan.
 Pasir laut banyak dimanfaatkan masyarakat untuk digunakan dalam pembangunan rumah, jembatan dan berbagai bangunan lainnya. Sampai pada titik tertentu, pengambilan pasir sudah sampai pada ambang kritis. Terbukti dengan terkikisnya pesisir pantai di beberapa daerah karena pengambilan pasir yang terus dilakukan. Di beberapa wilayah, pasir laut bahkan diambil secara beramai-ramai oleh berbagai pihak sehingga perubahan ketinggian pasir sudah mengalami penurunan mencapai 3 meter. Sebagian masyarakat mengambil pasir untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan sebagian lagi mengambil untuk dijual kepada pihak yang membutuhkan pasir laut.
Pasir laut banyak dimanfaatkan masyarakat untuk digunakan dalam pembangunan rumah, jembatan dan berbagai bangunan lainnya. Sampai pada titik tertentu, pengambilan pasir sudah sampai pada ambang kritis. Terbukti dengan terkikisnya pesisir pantai di beberapa daerah karena pengambilan pasir yang terus dilakukan. Di beberapa wilayah, pasir laut bahkan diambil secara beramai-ramai oleh berbagai pihak sehingga perubahan ketinggian pasir sudah mengalami penurunan mencapai 3 meter. Sebagian masyarakat mengambil pasir untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan sebagian lagi mengambil untuk dijual kepada pihak yang membutuhkan pasir laut.
B. Pemanfaatan Non-Ekstraktif
Pemanfaatan sumberdaya yang ada di laut tidak selalu dengan cara mengambil sumberdaya yang dibutuhkan tersebut. Terdapat berbagai jenis pemanfaatan sumberdaya dengan cara mengambil manfaat dari nilai-nilai dan fungsi yang diberikan sumberdaya tanpa mengambil sumberdaya tersebut. Pemanfaatan jenis itu dikenal dengan pemanfaatan non-ekstraktif. Berikut beberapa contoh jenis-jenis pemanfaatan non-ekstraktif.
Pemanfaatan sumberdaya laut dalam bentuk kegiatan pariwisata mengambil manfaat dan fungsi dari nilai-nilai keindahan yang terdapat pada lingkungan laut. Keindahan alam laut dapat diperoleh melalui kegiatan wisata pantai, panorama pantai, selancar, game fishing, dan selam. Pariwisata laut atau bahari juga meliputi kegiatan berjemur dan berenang di tepi pantai, serta fotografi bawah laut atau taman laut. Kegiatan wisata tidak hanya dinikmati oleh wisatawan dari mancanegara tetapi juga oleh masyarakat sekitar objek wisata bahari. Kegiatan wisata memberikan pengalaman menyenangkan bagi pengunjung sehingga berpengaruh terhadap kesegaran pikiran para pengunjung setelah sekian waktu penat dengan rutinitas pekerjaan masing-masing
- Pendidikan non ekstraktif
Manfaat berupa ilmu pengetahuan juga bisa diperoleh dari laut melalui kegiatan pendidikan tanpa mengambil sumberdaya yang ada. Kapal Kalabia yang beroperasi di Raja Ampat merupakan salah satu contoh aktivitas pendidikan non-ektraktif di atas laut. Kapal tersebut berlayar berkeliling perairan Raja Ampat sambil melangsungkan aktivitas belajar bagi anak usia sekolah di atas Kalabia. Selain itu, proses pendidikan banyak berlangsung di perairan dalam rangka mengetahui berbagai aspek tentang laut dan berbagai interaksi antar spesies dan antar ekosistem dalam laut. Edukasi bahari juga mulai dikembangkan di berbagai daerah di tanah air, dimana berlangsung aktivitas belajar sambil rekreasi di pesisir sambil mengunjungi spot-spot wisata bahari yang memberikan layanan pengetahuan kebaharian.
Laut juga bisa menjadi tempat untuk acara sosial seperti di berbagai tempat di nusantara. Kegiatan sosial tersebut lebih dominan aktivitas budaya masyarakat lokal seperti di Jawa, Bali dan sebagian Sulawesi. Aktivitas budaya tersebut misalnya melepas sesajen ke laut atau perayaan acara adat tertentu. Selain itu acara sosial lainnya yang memanfaatkan laut di antaranya perlombaan dayung atau lomba perahu dan sebagainya.
Hal menarik lainnya yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat terhadap laut adalah olahraga air. Berbagai jenis olahraga air yang sekaligus menjadi bagian dari kegiatan wisata bahari seperti water scooter, seabob, sausage boat, banana boat, water tricycle, wind surfing, surfboarding, paddle board, parasiling, kayaking. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan olahraga air laut tersebut di antaranya kesehatan psikologis karena telah melewati permainan yang menyenangkan. Manfaat lain yang dipercaya secara medis akan diperoleh dengan berolahraga di air laut adalah kesehatan fisik karena kandungan air laut berbeda dengan air tawar, sehingga memberikan efek berbeda setelah mandi atau berolehraga di air laut.
Pemanfaatan laut untuk perhubungan merupakan pemanfaatan yang paling dominan terjadi di laut karena daratan satu pulau dengan pulau lain dihubungkan oleh laut. Pemanfaatan media air laut ini tidak mengambil sumberdaya air laut itu sendiri. Perhubungan laut dilakukan oleh mesyarakat dengan menggunakan sampan, perahu maupun kapal dalam ukuran yang bervariasi. Laut dimanfaatkan fungsinya sebagai alur pelayaran agar masyarakat bisa terhubung dengan daerah lainnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
- Penelitian non-ekstraktif.
Laut menyimpan berbagai pengetahuan baik yang sudah tergali maupun yang masih terpendam. Karena itu penelitian tentang hal yang berhubungan dengan laut terus dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian baik dari perguruan tinggi, maupun lembaga penelitian lainnya. Di antara penelitian tersebut ada yang jenis penelitian yang hanya menggunakan laut sebagai objek penelitian tanpa mengambil sumberdaya apapun dari laut, penelitian ini termasuk jenis kegiatan yang non-ekstraktif.
Referensi :
CTC. 2016. Pengelolaan Kegiatan Pariwisata Bahari di Dalam Kawasan Konservasi perairan. Modul Pelatihan Pariwisata Bahari Berkelanjutan. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
Nattasya, Gesha. “Energi Laut, Alternatif Penyedia Sumber Energi Terbarukan”. 17 Januari 2017. http://www.kompasiana.com/geshayuliani/energi-laut-alternatif-penyedia-sumber-energi-terbarukan_551abf8681331137489de0e3
Puryono, Sri. 2016. Mengelola Laut untuk Kesejahteraan Rakyat. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Putra, Muhammad Firman Eko. “Potensi Energi Terbarukan Dari Laut”. 17 Januari 2017. http://membunuhindonesia.net/2016/01/potensi-energi-terbarukan-dari-laut/
www.matarmnews. “Penyelundupan Ribuan Terumbu Karang Berhasil Digagalkan”. 25 Januari 2017. https://mataramnews.co.id/nusa-tenggara-barat/item/7270-penyelundupan-ribuan-terumbu-karang-berhasil-digagalkan
 Pulau Tidung yang indah dengan pesona pantai pasir putih, dan laut yang jernih serta dasar laut yang landai, menjadi pilihan warga ibukota untuk mengunjunginya di saat liburan atau berwisata. Penduduk pulau ini cukup padat dan berpendapatan dari jasa wisata, perdagangan dan juga nelayan. Terdapat berbagai fasilitas publik dan kantor pemerintahan serta fasilitas pendidikan. Tanahnya yang subur menjadikan hampir keseluruhan pulau tertutup pepohonan yang membuat cuaca sejuk meskipun di tengah laut. Kesuburan tanahnya menjadikan salah satu komoditas pangan tumbuh subur disini. Ketika mendengar nama pulau ini disebut, maka ingatan seseorang yang pernah kesini akan langsung tertuju pada “Jembatan Cinta” yang menghubungkan Pulau Tidung dengan sebuah pulau kecil eksotis di sebelahnya.
Pulau Tidung yang indah dengan pesona pantai pasir putih, dan laut yang jernih serta dasar laut yang landai, menjadi pilihan warga ibukota untuk mengunjunginya di saat liburan atau berwisata. Penduduk pulau ini cukup padat dan berpendapatan dari jasa wisata, perdagangan dan juga nelayan. Terdapat berbagai fasilitas publik dan kantor pemerintahan serta fasilitas pendidikan. Tanahnya yang subur menjadikan hampir keseluruhan pulau tertutup pepohonan yang membuat cuaca sejuk meskipun di tengah laut. Kesuburan tanahnya menjadikan salah satu komoditas pangan tumbuh subur disini. Ketika mendengar nama pulau ini disebut, maka ingatan seseorang yang pernah kesini akan langsung tertuju pada “Jembatan Cinta” yang menghubungkan Pulau Tidung dengan sebuah pulau kecil eksotis di sebelahnya. Adalah di Pulau Tidung terdapat varietas tumbuhan sejenis porang yang tumbuh subur dan liar hampir di sebagian besar daratan pulau yag tidak terdapat bangunan di atasnya. Belum pasti apakah jenis itu adalah porang yang harganya saat ini Rp.10.000 hingga Rp.13.000 per kg basah dan siap panen, atau Rp.55.000 sampai Rp.65.000 per kg untuk yang iris kering (✔️ Harga Porang Basah dan Kering Bulan Ini Desember 2023 | HargaBulanIni.com). Tetapi yang pasti bahwa tumbuhan ini tumbuh subur di pulau Tidung, dan sampai saat ini menurut keterangan beberapa warga, belum pernah ada yang membelinya, sehingga masyarakat juga tidak tau bahwa tumbuhan itu bernilai ekonomis tinggi. Dari tampilan tumbuhan yang tumbuh liar ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat belum mengetahui nilai ekonomisnya.
Adalah di Pulau Tidung terdapat varietas tumbuhan sejenis porang yang tumbuh subur dan liar hampir di sebagian besar daratan pulau yag tidak terdapat bangunan di atasnya. Belum pasti apakah jenis itu adalah porang yang harganya saat ini Rp.10.000 hingga Rp.13.000 per kg basah dan siap panen, atau Rp.55.000 sampai Rp.65.000 per kg untuk yang iris kering (✔️ Harga Porang Basah dan Kering Bulan Ini Desember 2023 | HargaBulanIni.com). Tetapi yang pasti bahwa tumbuhan ini tumbuh subur di pulau Tidung, dan sampai saat ini menurut keterangan beberapa warga, belum pernah ada yang membelinya, sehingga masyarakat juga tidak tau bahwa tumbuhan itu bernilai ekonomis tinggi. Dari tampilan tumbuhan yang tumbuh liar ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat belum mengetahui nilai ekonomisnya.









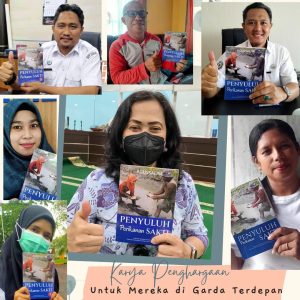
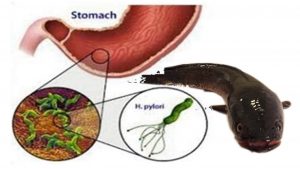
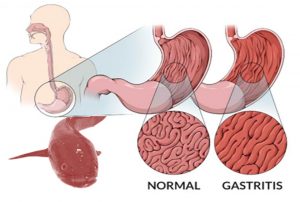






Komentar Terbaru